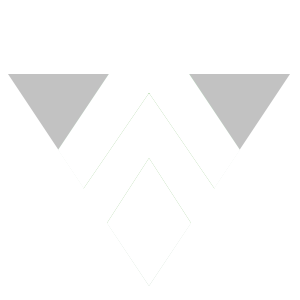Oleh: Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag. MA *
Kata egaliter berasal dari bahasa Prancis “égal” yang berarti “sama”. Egalitarianisme adalah aliran pemikiran dalam filsafat politik yang memprioritaskan kesetaraan sosial bagi semua orang. Ciri utama doktrin egaliter adalah gagasan bahwa semua manusia adalah setara dalam nilai dasar atau status moral. Egalitarianisme adalah doktrin bahwa semua warga negara harus diberikan hak yang setara.
Egalitariansme Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), egalitarianisme adalah doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajat.
Sebagai aliran dalam filsafat, istilah egalitarianisme memiliki dua definisi. Pertama, egalitarianisme sebagai doktrin politik bahwa semua orang harus diperlakukan secara sama dan memiliki hak politik, ekonomi, sosial dan sipil yang sama.
Kedua, egalitarianisme sebagai filosofi sosial yang mendukung penghapusan kesenjangan ekonomi di antara orang-orang, atau biasa disebut egalitarianisme ekonomi. Beberapa sumber ilmiah mendefinisikan egalitarianisme sebagai kesetaraan yang mencerminkan keadaan alami manusia.
Ada beberapa bentuk kesetaraan. Di antaranya ” kesetaraan manusia dan kesetaraan sosial. Dalam hal kesetaraan manusia, Bill of Rights Inggris tahun 1689 dan Konstitusi Amerika Serikat menggunakan istilah orang (person) dalam hal yang berkenaan dengan hak-hak dan tanggung jawab fundamental. Istilah pria laki-laki (men) dalam Bill of Rights Inggris merujuk pada pria yang diadili karena pengkhianatan; dan aturan perwakilan proporsional Kongres dalam Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat.
Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat juga menggunakan istilah orang (person) dalam pengaturan yang menyatakan bahwa “Negara bagian mana pun tidak boleh merampas kehidupan, kebebasan, atau properti setiap orang, tanpa proses hukum yang semestanya; atau menyangkal kepada setiap orang dalam yurisdiksinya perlindungan hukum yang sama”.
Bagaimana Islam memandang kesetaraan ini? Berbicara tentang egalitarian, Islam sangat teguh dalam memaknai bahwa semua umat manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhannya. Apa pun kedudukan manusia di bumi ini, serendah atau setinggi apa pun status sosial mereka, mereka tetap memiliki kesempatan yang sama contohnya dalam hal beribadah kepada Allah SWT.
Salah satu prinsip utama egalitarianisme adalah bahwa semua orang pada dasarnya setara. Setiap orang harus diperlakukan sama dan memiliki kesempatan serta akses yang sama dalam masyarakat, apa pun jenis kelamin, ras, atau agamanya. Dapat kita simak misalnya, dalam ibadah haji, mereka memakai pakaian ihram yang sama (warna serbaputih) dengan Semangat egalitarianisme telah banyak disebutkan dalam dalil-dalil shahih.
Tulisan ini menyunting beberapa teks ayat al-Quran yang mengajarkan kesetaraan manusia dalam kehidupan sosial. Al-Quran menggariskan bahwa manusia yang diciptakan sebab adanya laki-laki dan perempuan — dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, untuk saling mengenal (Q.s. al-Hujurat/49:13).
“Fal yanzhuri al-insánu min má khuliqa. Khuliqa min máin dâfiqin. Yakhruju min baini al-sulbi wa al-tarâib–hendaklah manusia memikirkan dari apa dirinya dijadikan. Manusia dijadikan dari air yang terpancar. Keluar dari antaran tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan” (Q.s. al-Thâriq/86:5-7). “Innâ kbalaqnâ al-insâna min sulâkatin min thîn–sesungguhnya Kami menciptakan manusia dari saripati tanah yang tersaring” (Q.s. al-Mu’minûna/23:12). “Waja’ala anslahû min sulâlatin min máin mahînin–dan Allah menjadikan anak turunan Adam dari saripati air yang hina” (Q.s. al-sajadah/32:8).
Keterangan ayat-ayat di atas sesungguhnya menyatakan eksistensi manusia yang didasari kesetaraan–egaliter. Semua manusia itu sama. Yaitu sama-sama diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sama-sama dijadikan dari saripati tanah yang tersaring, dari saripati air yang hina.
Atas dasar kesetaraan itu, bahkan Rasulullah Saw dalam khuthbah wada’ menyampaikan penegasannya dan sebagai sebagai tafsir utama atas keterangan ayat Q.s. 49:13 di atas, yaitu “Mâ al-farqu baina al-‘arabi wa al-‘ajami illa bi al-taqwá–tidak ada perbedaan antara arab dan non arab kecuali dengan takwa. Juga dalam hal hukum, Beliau tidak mengecualikan putrinya dari hudud sekiranya Fsthimah melanggar hukum. “Law saraqat fâthimatu laqatha’tu yadahâ–sekiranya Fathimah mencuri pasti Aku potong tangannya”.
Keterangan teks ayat al-Quran dan potongan-potongan hadis di atas menyebut bangsa dan suku dalam kesetaraan itu. Tidak ada pengecualian dari segi bangsa dan suku itu. Adapun pengecualiannya bertajuk kemuliaan di sisi Allah adalah sebab amalnya dinilai karena paling takwa. Paling takwa artinya paling intens beragama. Yakni paling intens mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena paling intens taqarrub itu, maka hatinya menjadi paling baik. Itulah yang paling mulia dalam tilikan Allah Swt.
Suku-bangsa adalah identitas kelahiran. Sementara siapa pun yang lahir ke permukaan bumi ini, tentu melalui rahim ibunya, tidak ada yang memesan supaya bisa lahir di dan dengan identitas suku-bangsa tertentu. Ini menunjukkan bahwa kelahiran adalah wujud takdirnya Allah Swt. Jangankan suku-bangsa, bahkan agama sekali pun tidak ada yang bisa request perspektif kelahiran. Kelahiran adalah penegasan kemutlakan Tuhan yang tak bisa diganggu gugat.
Dalam hal agama-agama, semangat egalitarianisme telah banyak disebutkan dalam dalil-dalil shahih. Salah satunya yaitu Surat Al-Baqarah ayat 62 yang artinya “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang sabi’in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.”
Islam juga mengajarkan tasâmuh dan ‘adâlah. Tasámuh atau toleran dalam beragama adalah sikap tenggang terhadap orang lain untuk menganut, memahami, mendalami, dan mengamalkan ajaran agamanya, sebagai mana kita juga berbuat begitu. Kita banyak membaca teks keterangan ayat “lakum dînukum waliyadîn–bagimu agamamu dan bagiku agamaku, lanâ a’mâlunâ walakum a’mâlukum–bagi kami amal kami dan bagiku amal kamu”.
Dalam hal keadilan, al-Quran juga memerintahkan supaya pengimannya berlaku adil. “Yâ ayyuhallazîna âmanû kûnû qawwâmîna lillâhi syuhadâa bi al-qisthi wa lâ yajrimannakum syanaânu qaumin ‘alâ allâ ta’dilû, i’dilû, huwa aqrabu li al-taqwâ wattaqulláh, innallâha khabírun bimâ ta’malûn–Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan jangan lah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.s. al-Mâidah/5:8). Selain keterangan ayat di atas, masih banyak lagi dalil senada dengan itu.
Itu sebabnya akan dinilai sangat tercela jika ada yang mengotak-atik kesetaraan dengan dalil suku-bangsa dan agama. Karena semua kita hanya menjalankan kemutlakan takdir Tuhan tadi, baik dalam eksistensi suku-bangsa, maupun agama. Takdir dari sisi kelahiran jasmaniah yang menyebabkan identitas suku-bangsa ini adalah jasmani–zhahir.
Selanjutnya, setelah kesetaraan dari sisi kelahiran identitas lahiriah ini, pada manusia ada satu eksistensi yang sama-sama datang dari Tuhan, yaitu Ruh, kesetaraan Ruh. Ruh ini menurut al-Quran, sifat wujudnya adalah cahaya (Q.s. al-syúrá/42:52). Ruh ini datang dari asal yang sama yaitu Tuhah, Allah Swt. Dalam semua kitab suci dan dalam semua referensi kegamaan, disebutkam bahwa Ruh itu dari Tuhan, bukan dari yang lainnya. Tidak ada karena suku-bangsa tertentu, lalu yang satu Ruhnya dari Tuhan, dan yang lainnya dari jin. Lagi-lagi dari segi asal Ruh ini semua manusia setara.
Kemudian, pada Ruh itu ada dzat, atau rasa, atau nikmat. Sekali lagi wujud dzat ini sama. Sifat wujud dzat ini tidak bisa dilukis dengan sesuatu yang bersifat fisik atau materi. Karena dzat ini eksistensinya hanya bisa ditahu berupa rasa. Misalnya rasa manis, itu tidak fisikly, tetapi dapat dirasa wujudnya. Manis tidak bisa dijelaskan dengan definisi lughatan atau ishtilahan. tetapi hanya bisa dirasakan adanya.
Dzat ini dirasakan ada wujud bukan oleh fisik-lahiriah. Misalnya manis itu ada wujud rasanya bukan oleh lidah, tetapi oleh Ruh yang sedang eksis dalam tubuh manusia, meliputi lidah. Mengapa? Karena adanya dzat ini mengiringi diutusnya Ruh oleh Allah ke dalam tubuh manusia. Sama seperti pendengaran dan penglihatan, wujudnya mengiringi Wujudnya Ruh dalam tubuh manusia (Q.s. al-Sajadah/32:9).
Jika Ruh itu sedang tidak eksis dalam tubuh manusia karena ditahan–wafat oleh Allah pada saat kematian atau saat tidur (Q.s. al-Zumar/39:42), maka pendengaran, penglihatan, dan rasa tadi tidak ada. Itu artinya yang merasa manis bukan lidah, yang mendengar bukan telinga, dan yang melihat bukan mata, tetapi dzat yang wujudnya tak terpisah dengan Ruh.
Hal ini sama pada semua wujud diri pada manusia di seluruh permukaan bumi ini. Sama atau setara yang dimaksud adalah lintas suku-bangsa dan agama. Artinya seseorang bersuku-bangsa dan agama apa pun, Ruh dan Dzar–rasa tadi sama–setara wujudnya.
Kembali ke bahasan tentang kesetaraan–egaliter menurut Islam. Bahwa ditinjau dari sisi mana pun, manusia itu sama. Baik dari sisi jasmaniah maupun dari sisi ruhaniahnya, zhair dan batinnya. Identitas lahiriah pada manusia itu hanya sebatas untuk saling mengenal.
Kesetaraan ini pula berlaku sama di hadapan Allah. Bahwa Allah itu Wujud-Nya tidak tersusun dari materi (fallâhu laisa lahû ‘anâshirun mina al-ajsâm). Maka eksistensi materi pada manusia tidak dinilai oleh Allah. Maka oleh karena itu, dalam ibadah sekalipun tidak yang bersifat lahiriah yang ditilik dan dinilai oleh Allah. “Innallâha lâ yanzhuru ilâ shuwarikum walâ ilâ ajsâmikum, walâ ilâ a’mâlikum walâkin yazhuri ilâ qulûbikum waniyyatikum–sesungghnya Allah tidak memandang kepada rupa, jasmani, dan amalmu. Tetapi Allah memandang kepada hati dan niatmu”.
Sekali lagi, kesetaraan manusia di sisi Allah sama. Yang bersifat fisik seperti suku-bangsa tidak laku di sisi Allah. Dalam hal ini kita bisa melihat adilnya Allah kepada semua makhluk dan hamba-Nya. Ruh itu hamba sedang berada dengan makhluk yang bernama manusia dalam tubuhnya. Ruh tidak punya pilihan untuk bertugas dan lahir dalam dan dari tubuh manusia yang mana. Maka oleh karena itu bukan eksistensi yang bersifat fisik seperti suku-bangsa yang dinilai Allah. Melainkan kinerja hati yang ditilik oleh-Nya.
Maka sebab itu, sangat tidak patut kita merasa lebih mulia dan lebih tinggi dari manusia lainnya karena identitas suku-bangsa. Lalu kita merasa pantas pula untuk merendahkan manusia lainnya karena identitas itu.
Kalau pun kita dimuliakan oleh orang lain, itu karena Allah memuliakan kita, sebab takwa yang menjadi kinerja hati. Pasti itu artinya bukan karena suku-bangsa kita. Juga asal-usul kemuliaan kita itu, karena kita diberikan pengajaran lewat kenabian utusan Allah yang mengajarkan kitab dan hikmah
“Mâ kâna libasyarin an yu’tiyallâhu al-kitâba wa al-hukma wa al-nubuwwata tsumma yaqûla li al-nâsi kûnû ‘ibâdan li min dûnillâhi–tidak pantas bagi manusia yang diberi kitab, hikmah, dan kenabian kemudian berkata kepada manusia (lainnya) jadilah abdi/hamba untukku bukan menjadi hamba Allah” (Q.s. Âli ‘Imrân/3:79).
Ayat ini menggambarkan bahwa manusia itu cenderung menindas derajat orang lain. Manusia cenderung memperbudak orang lain. Bahkan saking jumawahnya manusia itu menyuruh manusia lainnya untuk menjadi hambanya. Ayat ini pula secara tersirat bahwa perilaku memperbudak orang lian, dilakukan manusia bahkan serelah dia mendapat pengajaran dari Allah melalui kenabian. Maksudnya manusia cenderung menggunakan ajaran agama untuk meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain.
Terdapat banyak hadis tentang kesetaraan–egaliter sebagai relevansi teks-teks ayat al-Quran di atas. Hadits riwayat Ahmad dijelaskan mengenai egalitarianisme dalam Islam, selain hadis-hadis di atas. “‘An ‘uqbata ibni ‘âmiri al-juhaniyyi qâla rasûlullâhi shallallâhu ‘alaihi wasallam, inna ansâbakum hâdzihî laisat bimasabbatin ‘alâ ahadin kulluhum banû âdama thaffu al-shâ’i lam tamlaûhu laisa liahadin ‘alâ ahadin fadhlun illâ bidînin aw taqwâ-, rawâhu ahmad-Dari ‘Uqbah ibn ‘Amir al-Juhani, Rasulullah bersabda nasab-nasab kalian tidak bisa dijadikan alasan untuk mencaci-maki seseorang. Manusia itu setara (dalam hal nasab) bagai permukaan air di ember yang penuh dan semuanya adalah keturunan Adam. Tidaklah seseorang lebih unggul dari yang lainnya kecuali dalam hal agama dan ketakwaannya kepada Allah.” (HR. Aḥmad).
Argumen-argumen naqli di atas sulit untuk digugurkan atau dibantah bahwa manusia itu setara di mata Allah, dan harus setara di mata sesamanya. Di hadapan Allah perbedaan hanya diinstrumeni dengan kinerja hati pada manusia yang intens hadir kepada Allah, namanya takwa. Instrumen ini jika dicapai di sisi Allah, otomatis akan mulia di sisi manusia. Karena takwa itu intinya bersihnya hati dari penyakitnya. Indikator mutlak bersihnya hati dari penyakitnya itu adalah tiadanya perilaku-perilaku emosional, kemarahan, ketersinggungan (ammarah), ‘ujub–bangga diri, riya–gemar dipuji, takabbur–membesar-besarkan diri, hasud–iri dengki–tidak senang dengan kelebihan orang lain, tamak-loba–serakah dan kikir, dan sombong (lawwamah).
Intinya, kemualiaan itu pemberian Allah karena iman, ilmu, amal shaleh, yang disimpul menjadi takwa. Kemuliaan tidak bisa dengan rekayasa dan seleberisasi. Jadi paham egaliter sebenarnya ungkapan rasa setiap manusia. Kesetaraan inilah yang membedakan Islam dengan Hindu yang menganut paham Kasta atau strata.
Setiap diri pada manusia, pandai merasa tentang dirinya, apakah dia intens atau nihil menghadap Allah. Doktrin tentang kemuliaan orang lain di mata seseorang melahirkan ketidaktulusan. Beda antara orang yang memuliakan orang lian karena ketulusan sebab menyaksikan kesalehannya, dengan memuliakan orang lain karena terpaksa sebab takut dan iming-iming surga serta ancaman neraka, juga sebab seleberisasi.
Seleberisasi adalah upaya meng-artis-kan diri, memuliakan diri, meng-kelastinggi-kan diri, dengan rekayasa menggunakan berbagai properti. Properti paling utama seleberisasi ini adalah mencantolkan diri, atau mengaitkan diri kepada orang yang telah mulia dan dimuliakan, kepada orang yang punya nama besar dan derajat yang tinggi. Orang semacam ini tak ubahnya parasit yang menumpang hidup dan subur di pohon yang bukan dirinya.
Properti lain misalnya, menggunakan jasa master of ceremoni dengan retorika bahasa sanjungan di muka umum. Selanjutnya, properti yang paling tidak berkelas adalah dengan mengarak diri di tengah-tengah keramaian, diarak dengan umbul-umbul, diiringi pengawal yang sangat ramai, diarak dengan tabuhan bunyi-bunyian yang hiruk-pikuk, lalu yang bersangkutan dipayungi dengan payung kehormatan. Lalu berjalan dengan menggagahkan diri bak FIR’AUN yang minta sembah, dan seterusnya yang senada dengan itu.
Yuk secara alami kita menyetarakan diri dengan sesama. Biarkan Allah yang memuliakan kita dan menautkan hati orang lain atas diri kita yang telah dimuliakan-Nya. Yuk kita raih jadi seleberitis di langit karena ketakwaan, yang karenanya kita akan jadi artis di bumi. Dengan itu tidak perlu kita melakukan seleberisasi–mengartiskan diri, dengan mengarak diri sendiri di tengah-tengah keramaian.
* Penulis adalah Guru Besar Ilmu al-Quran dan Tafsir sekaligus Rektor IAIN Pontianak, dan Ketua PWNU Kalimantan Barat